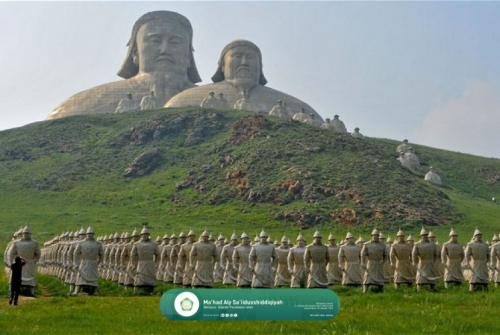Gus Dur; Sang Pembaru dari Pesantren
Ma’had Aly – Siapa yang tidak kenal KH. Abdurahman Wahid. Beliau merupakan tokoh fenomenal yang sangat dikagumi oleh penduduk Indonesia khususnya, bahkan nama beliau sudah tersohor sampai ke penjuru dunia.
Dalam buku Intelektualisme Pesantren, disebutkan bahwasanya KH. Abdurahman Wahid bernama lengkap Abdurahman “Addakhil”. Kata “Addakhil” yang mempunyai arti “Sang Penakluk”, nama tersebut diambil oleh Wahid Hasyim, orang tuanya dari seorang perintis Dinasti Umayyah yang menancapkan tonggak kejayaan Islam di Spanyol. Kemudian nama belakang ”Addakhil” tidak cukup dikenal di masyarakat maka diganti dengan “Wahid”, Abdurahman Wahid, dan kemudian lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Kata “Gus” merupakan panggilan kehormatan khas pesantren sebagai anak kiai yang berarti “abang” atau “mas”.
KH. Abdurahman Wahid atau Gus Dur merupakan putra pertama dari enam bersaudara yang dilahirkan di Denayar Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Desember 1940. Gus Dur merupakan keturunan “darah biru”. Ayahnya, KH. Wahid Hasyim adalah putra dari KH. Hasyim Asy’ari pendiri dari organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dan juga pendiri dari Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan ibunya, Ny. Hj. Sholehah merupakan pendiri Pesantren Denayer Jombang. KH. Bisri Syamsyuri kakek Gus Dur dari pihak ibunya juga merupakan tokoh NU yang menjadi Rais ‘Aam PBNU setelah KH. Abdul Wahab Hasbullah. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwasanya Gus Dur merupakan cucu dari dua ulama NU sekaligus, dan dua tokoh bangsa Indonesia.
Pada pendidikannya, Gusdur kecil belajar pada sang kakek, KH. Hasyim Asy’ari. Saat satu rumah Gus Dur diajarkan membaca al-Qur’an. Dalam usia lima tahun Gus Dur telah lancar dalam membaca al-Qur’an. Menurut Ahmad Baso, dalam bukunya Islam Nusantara menyebutkan bahwa, Gus Dur belajar tidak hanya melalui sekolah atau madrasah, tetapi juga melalui pengajian puasa yang berpindah-pindah atau yang sering dikenal dengan sebutan pesantren kilat. Seperti contoh, tahun ini beliau ikut pengajian puasa di Pesantren Sarang, mengaji kepada Kyai Zubair Dahlan, beliau merupakan seorang ulama yang ahli dalam ilmu fiqih “si jago fiqih”. Kemudian pada tahun berikutnya beliau mengaji puasa dipondok lain dengan spesialisasi Ihya Ulumuddin. Kemudian ditahun berikutnya Gus Dur belajar tafsir dari kiai lain lagi.
Setelah lulus Sekolah Dasar di Jakarta, beliau melanjutkan belajarnya di Yogyakarta pada tahun 1953 untuk masuk SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) sekaligus mondok di pesantren Krapyak. Di sekolah ini Gus Dur pertamakali belajar bahasa Inggris. Pada saat menjadi siswa sekolah lanjutan pertama tersebut, hobi membacanya semakin meningkat berkat dorongan dari gurunya seperti untuk menguasai bahasa Inggris, sehingga dalam waktu satu sampai dua tahun Gus Dur menghabiskan beberapa buku dalam bahasa Inggris. Dari paparan ini tergambar dengan jelas kekayaan informasi dan keluasan wawasan Gus Dur.
Setelah tamat dari SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama), Gus Dur melanjutkan pendidikanya di Pesantren Tegal Rejo, Magelang Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. Chudhari. KH. Chudhari inilah yang mengajarkan kepada Gus Dur praktik-praktik mistik. Di bawah bimbingan beliau Gus Dur mulai berziarah ke makam-makam keramat para wali di Jawa. Setelah dua tahun di Tegal Rejo, Gus Dur kembali ke Jombang dan tinggal di Pesantren Tambak Beras pada saat usia mendekati 20 tahun. Pesantren ini milik pamannya, KH. Abdul Fatah. Di sana Gus Dur diangkat menjadi seorang ustad dan ketua keamanan.
 Pada saat usia 20 tahun Gus Dur berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskannya ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Sesampainya Gus Dur di Mesir beliau merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk Universitas al-Azhar, akan tetapi harus terlebih dahulu masuk Aliyah (semacam sekolah persiapan). Di sana Gus Dur merasa bosan karena harus mengulangi mata pelajaran yang telah ditempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan pusat pelayanan informasi Amerika (USIS). Kemudian pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak, beliau masuk Departement of Relegion, Universitas Baghdad, di sana Gus Dur mempuyai pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota seribu satu malam ini beliau mendapatkan ransangan intelektual yang tidak didapatkanya pada saat di Mesir. Gus Dur mempelajari ajaran dari Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti NU. Di sinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya. Kondisi politik yang terjadi di Irak turut memengaruhi perkembangan pemikiran politik Gus Dur pada saat itu.
Pada saat usia 20 tahun Gus Dur berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, yang kemudian diteruskannya ke Mesir untuk melanjutkan studi di Universitas al-Azhar. Sesampainya Gus Dur di Mesir beliau merasa kecewa karena tidak dapat langsung masuk Universitas al-Azhar, akan tetapi harus terlebih dahulu masuk Aliyah (semacam sekolah persiapan). Di sana Gus Dur merasa bosan karena harus mengulangi mata pelajaran yang telah ditempuhnya di Indonesia. Untuk menghilangkan kebosanan Gus Dur sering mengunjungi perpustakaan dan pusat pelayanan informasi Amerika (USIS). Kemudian pada tahun 1966, Gus Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di Irak, beliau masuk Departement of Relegion, Universitas Baghdad, di sana Gus Dur mempuyai pengalaman hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota seribu satu malam ini beliau mendapatkan ransangan intelektual yang tidak didapatkanya pada saat di Mesir. Gus Dur mempelajari ajaran dari Imam Junaid al-Baghdadi, seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti NU. Di sinilah Gus Dur menemukan sumber spiritualitasnya. Kondisi politik yang terjadi di Irak turut memengaruhi perkembangan pemikiran politik Gus Dur pada saat itu.
Sepulang dari Timur Tengah, yaitu di Cairo dan Baghdad, Gus Dur berusaha memperoleh jatah program doktor di Canada atau Amerika Serikat. Akan tetapi semua rencananya gagal karena ketika melihat keadaan pondok pesantren di awal-awal tahun tujuh puluhan, Gus Dur melihat adanya krisis di pondok pesantren. Yaitu pada pendidikan, di mana pesantren mulai mementingkan ijazah tertulis melalui ujian sekolah formal saja. Dan hanya menjadikan penguasaan ilmu-ilmu agama menjadi perhatian kedua, yang lebih dipentingkan hanyalah lulus ujian tertulis. Adapun yang tadinya ijazah lisan dari kiai yang berisi pelajaran untuk membaca dan menerangkan kitab kini hanya digantikan dengan ijazah Negara yang tidak bisa menjamin kemampuan pemiliknya untuk mengajarkan kitab sekecil apapun. Di samping terjadi krisis dari pendidikan, pada saat itu juga terdapat krisis pada ekonomi pesantren di desa-desa. Hal itu bisa terjadi dikarenakan hilangnya orang-orang kaya muslim dan semakin menurunya tingkat kehidupan di desa. Semua itu berimbas pada pesantren yang ada di desa, karena pendukung keuangan pesantren semakin menipis dan dukungan mereka akan dititikberatkan pada dukungan moral, karena tidak mampu menyediakan dukungan keuangan seperti dahulu. Belum lagi dengan adanya krisis budaya, karena derasnya arus budaya asing yang masuk ke pesantren sebagai limbah dari banjir diluar pesantren. Ditambah juga dengan adanya krisis politik yang terjadi karena banyaknya pesantren yang ingin dekat dengan pemerintah. Untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi di pesantren tersebut Gus Dur bertekat bulat untuk memperjuangkan kehidupan pesantren agar menjadi lebih baik kedepannya.
Dari kutipan di atas dapat dengan jelas menggambarkan jati diri seorang Gus Dur sebagai “pembaru dari pesantren” bukan sebagai “pembaru bagi pesantren”, seperti yang digelarkan kepada Dawam Rahardjo di tahun 1970-an atau Nurcholish Madjid pada 1980-an. Meskipun tetap mengakui sebagai pribadi yang sangat mencintai pesantren, namun Gus Dur mampu menggabungkan antara tradisi pesantren dengan dengan kehidupan dunia modern. Gus Dur sebagai sosok yang mempunyai akar tradisionalisme yang sangatlah kokoh di satu pihak, dan keluasan wawasan di dunia modern di pihak lain. Dari kombinasi dua arus tersebut Gus Dur menjadi pribadi yang sangat menghormati nilai-nilai demokrasi seperti komitmen dan penghargaan terhadap pluralisme, dimana diberikan kebebasan mengemukakan pendapat baik lisan maupun tulisan, kebebasan beragama, keadilan dan sebagainya.
Komentar dari Syarif Utsman Yahya yang dituliskan pada buku Gus Dur Lebih Memilih Kebenaran daripada Kekuasaan, ia menyebutkan bahwa pemikiran dan gagasan Gus Dur itu sangatlah banyak sekali, namun yang pada intinya Gus Dur menginginkan Islam sebagai agama rahmatan li al’alamin, agama yang menjadi rahmat sekalian alam. Dengan mengedepankan Islam sebagai agama rahmat, Islam akan mengayomi dan melindungi semua pihak, dan tidak ada yang merasa dirugikan, terancam bahkan teraniaya.
Oleh : Fahris Faizin, Semester IV