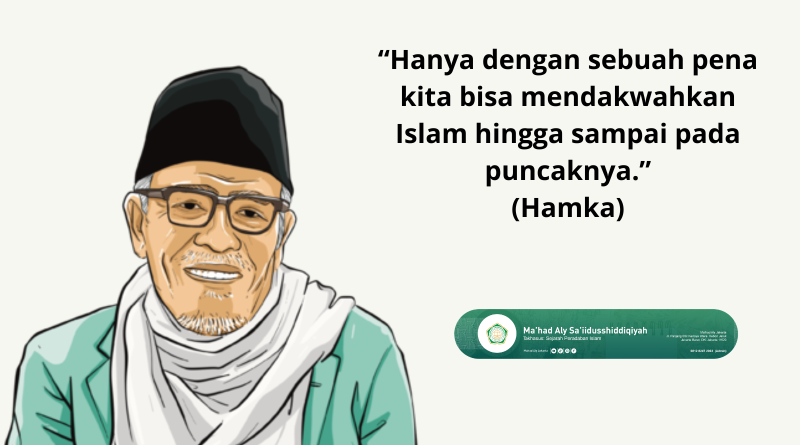Langit Pemikiran Buya Hamka: Antara Kalam, Pena, dan Perjuangan
MAHADALYJAKARTA.COM—Hamka adalah salah satu tokoh bangsa Indonesia sekaligus ulama yang diakui oleh dunia. Hamka dikenal sebagai seorang ulama, sastrawan, pemikir Islam, dan pejuang kemerdekaan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok beliau baik dari segi keteladanannya dan juga semangat kebangsaannya. Hamka bukan hanya sekedar tokoh ulama yang diakui oleh umat Islam tetapi seorang yang memberikan pengaruh besar dalam negeri, tafsir Al-Qur’an dan semangat kebangsaan.
Dari Padang Panjang ke Panggung Bangsa
Panggilan “Buya” pada Buya Hamka berasal dari tradisi masyarakat Minangkabau. Kata Buya adalah bentuk penghormatan yang berasal dari kata Arab Abi atau Abuya, yang berarti “ayah” atau “guru”. Dalam budaya Minangkabau, sebutan ini biasanya diberikan kepada ulama, orang terpandang, atau tokoh agama yang dihormati karena ilmunya. Sedangkan “Hamka” adalah akronim dari nama lengkap beliau, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dari situ, masyarakat lebih mudah menyebutnya dengan “Hamka”. Jadi, gabungan “Buya Hamka” adalah panggilan kehormatan yang menegaskan beliau sebagai ulama besar, guru masyarakat, sekaligus cendekiawan Muslim yang dihormati di Indonesia.
Buya Hamka adalah putra dari syekh Abdul Karim bin Amrullah dan Siti Safiyyah. Ayahnya adalah seorang ulama besar dan pelopor gerakan islam di Minangkabau. Buya hamka lahir pada tanggal 17 februari 1908 di kampung Molek Maninjau Sumatera Barat. Pada tahun 1929 tepatnya pada tanggal 5 April Hamka menikah dengan Siti Raham. Mereka menikah dalam usia yang sangat muda, saat itu Hamka berusia 21 tahun dan istrinya berusia 15 tahun, dalam pernikahan ini Hamka mempunyai 10 keturunan.
Hamka menjalani masa kecilnya di Maninjau. beliau sekolah dasar hanya sampai kelas 2 kemudian pada saat Hamka berusia 10 tahun ayahnya mendirikan muthalib di Padang Panjang sehingga masa kecilnya dia fokuskan untuk memperdalami agama dan belajar bahasa Arab. Tidak hanya sampai disitu ketika Hamka menginjak usia 16 tahun beliau merantau ke Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada HOS Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadikusumo, RM Soerjopranoto dan KH Fakhruddin. Pada saat itu pula Hamka banyak mengikuti berbagai diskusi training pergerakan Islam di Abdi Dharma Pakualam, Yogyakarta. Pada tahun 197 Hamka menjadi guru agama di perkebunan tinggi Medan, kemudian pada tahun 1929 mengajar di Padangpanjang, setelah itu menjadi dosen di Universitas Islam, Jakarta dan Universitas Muhammadiyah dari tahun 1957 sampai 1958.
Dunia Kepenulisan
Hamka terkenal sebagai penulis yang produktif. Beliau banyak menulis buku baik dalam bidang sastra ataupun agama. Karya Hamka yang paling terkenal di bidang tafsir adalah Tafsir Al-Azhar, Hamka menulis tafsir ini pada saat dipenjara oleh rezim Soekarno pada tahun 1960. Selanjutnya karya Hamka yang lainnya dalam bidang sastra di antaranya Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, buku ini menjelaskan tentang kisah cinta dan keadilan sosial yang menggambarkan konflik adat Minang dan modernitas. Selain itu karya lainnya ada juga Di bawah Lindungan Ka’bah, Merantau ke Deli, dan Siti Nurbaya. Hamka juga menulis biografi tokoh Islam, sejarah umat Islam, dan empat imam mazhab.
Jejak Politik
Hamka bukan hanya seorang sastrawan beliau juga aktif dalam perpolitikan. Hamka pernah menjabat sebagai pegawai tinggi agama dari tahun 1951 sampai 1960. Kemudian Pada 26 juli 1977 menteri agama Indonesia Prof. Dr. Mukti Ali melantik Hamka sebagai Ketua umum (MUI) Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1981, hamka meletakan jabatan itu karena nasehatnya tidak dipedulikan oleh pemerintah indonesia. Tidak hanya itu, Hamka juga seorang kader dan tokoh Muhammadiyyah.
Di Balik Jeruji Besi
Pada tahun 1964, Buya Hamka ditangkap oleh rezim orde lama karena dituduh terlibat dalam kegiatan politik yang berseberangan dengan pemerintah, terlebih lagi dengan kedekatan Buya Hamka dengan partai Masyumi yaitu partai Islam yang dilarang oleh pemerintah. Ideologi Hamka juga dianggap berseberangan dengan ideologi presiden Soekarno, terutama dalam hal pandangannya terhadap komunisme dan kebijakan nasakom (nasionalisme agama dan komunisme). Buya Hamka sangat menolak keras adanya komunisme karena menurutnya prinsip komunisme bertentangan dengan prinsip agama Islam. Hamka juga khawatir pendekatan nasakom bisa merusak aqidah umat Islam. Buya Hamka dipenjara tanpa melalui proses yang adil. beliau ditahan di rumah tahanan PRT Salemba Jakarta selama lebih dari 2 tahun (1966-1966). Alih alih meratapi nasib, Buya Hamka menggunakan waktunya didalam penjara untuk menulis, salah satu karya beliau yang ditulis selama di penjara adalah “Tafsir Al-Azhar”, sebuah tafsir Al-Qur’an lengkap dengan bahasa Indonesia. Beliau menulis tafsir itu dengan tangannya sendiri dan banyak dari bagian awal tafsir itu selesai justru saat Hamka berada di balik jeruji besi. Seperti yang pernah dikatakan Buya Hamka “Penjara bisa mengurung tubuhku tapi tidak dengan pikiranku”.
Namun sebenarnya Buya Hamka adalah sosok yang kurang tertarik terhadap kancah perpolitikan seperti yang pernah dituliskan oleh Roem di buku “70 tahun buya hamka” dalam buku tersebut Roem menuliskan kutipan pidato Buya Hamka yang bunyinya, “lapangan politik bukanlah bidangku, aku dikenal sebagai pujangga dan tetaplah pujangga, yang bersayap terbanglah laju, alat juangku tetaplah pena,” artinya, Buya Hamka tidak tertarik akan perpolitikan tetapi yang perlu diingat, beliau tidak bisa lepas dari perpolitikan selain latar belakangnya beliau juga seorang sejarawan.
Hamka sebagai Pemikir Integralis
Buya Hamka memperjuangkan persatuan agama dengan negara secara formal. Ada tiga alasan mengapa buya hamka tidak memisahkan antara agama dan negara. Pertama, Islam mencakup segala hal baik dunia maupun akhirat, privat atau publik. Kedua, banyak sekali ajaran Islam yang tidak bisa terwujud dengan sempurna tanpa keterlibatan negara. Alasan ketiga adalah secara historis Nabi Muhammad juga bersentuhan dengan politik kenegaraan. walaupun Hamka adalah seorang yang integralis, beliau menyadari bahwa Islam tidak memberikan aturan baku dan rinci tentang politik. Bagi Buya Hamka ini adalah kesempatan bagi umatnya untuk berijtihad dan membuat format pemerintahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam artian integralisme Buya Hamka tidak kembali ke masa lalu tapi integralisme yang modern.
Maaf Tanpa Syarat
Ketika Soekarno wafat pada tahun 1970, keluarga Soekarno meminta Buya Hamka untuk menjadi imam salat jenazah. Meskipun pernah diperlakukan tidak adil, Buya Hamka menerima permintaan itu dengan lapang dada dan memimpin salat jenazah bagi orang yang pernah memenjarakannya.
Wafatnya Buya Hamka
Buya hamka mengidap penyakit jantung. Kesehatannya menurun drastis pada tahun 1981 walaupun kesehatannya tidak kunjung membaik di akhir hayatnya Hamka tetap berkarya tetap aktif menulis dan berdakwah. Masa tuanya ia habiskan lebih banyak di Jakarta. Buya Hamka wafat pada 24 juli 1981 di Rumah Sakit Pertamina, Jakarta, dalam usia 73 tahun. Jenazah Buya Hamka di kebumikan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan.
Buya Hamka bukan hanya seorang yang nama yang ada dalam sejarah, beliau adalah seorang pejuang bangsa, pemilik pena dan seorang ulama yang berpendirian teguh. Hamka mengajarkan kepada kita bahwa hanya dengan sebuah pena kita bisa mendakwahkan Islam hingga sampai pada puncaknya. Dari beliau juga kita belajar bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri bahkan saat dibungkam. Warisan Buya Hamka akan terus hidup menerangi generasi yang haus akan ilmu dan keteladanan.
Referensi:
Gasong, D. 2018. Kritik Sastra. Yogyakarta: Deepublish.
Hamka, R. 2018. Pribadi dan Martabat Buya Hamka. Jakarta Selatan: Naora.
Mahendra, Y. I. 2022. Mewarnai Indonesia: Jejak Perjuangan dan Pemikiran Tokoh dalam Mengisi Kemerdekaan. Tangerang Selatan: YPM (Young Progressive Muslim).
Sugiharto, T. 2016. Ensiklopedi Pahlawan: Semangat Pahlawan Kemerdekaan Indonesia. Bandung Barat: SM Publishing.
Wibowo, C., & Utama, P. 2024. Menjadi Manusia Seutuhnya: Kontemplasi dan Refleksi sebagai Muslim. Lombok Barat: Rehal.
Kontributor: Siti Juwita, Semester III
Editor: S. Yayu. M