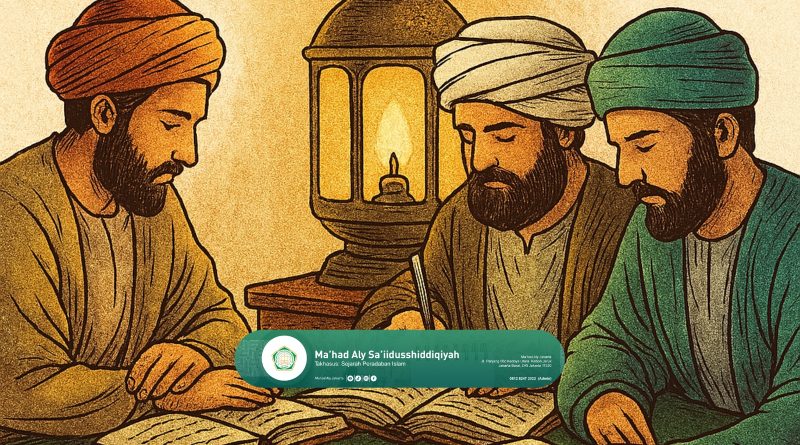Lentera Al-Andalus: Ulama Islam yang Menerangi Eropa
MAHADALYJAKARTA.COM—Ditengah kegelapan abad pertengahan eropa, sebuah peradaban gemilang bersinar di ujung barat benua: Al-Andalus. Dari abad ke-8 hingga ke-15, wilayah yang kini ia kenal sebagai Spanyol dan Portugal ini menjadi pusat ilmu, budaya, dan spiritualitas Islam. Di bawah naungan kekhalifahan Umayyah dan dinasti-dinasti berikutnya, ulama-ulama Al-Andalus seperti Ibnu Rusyd, Al-Zahrawi, dan Ibnu Al-Baitar tidak hanya menjaga api keislaman, tetapi juga menerangi Eropa dengan karya-karya monumental mereka. Mereka adalah lentera yang memancarkan cahaya filsafat, sains, dan adab, yang meninggalkan warisan menggema hingga masa kini.
Ibnu Rusyd: Filsuf yang menjembatani Akal dan Wahyu
Ibnu Rusyd, atau Averroes di Barat, lahir pada tahun 1126 M di Cordoba, pusat intelektual Al-Andalus. Berasal dari keluarga ulama fiqih Maliki, ia menjabat sebagai qadhi (hakim) di Sevilla dan Cordoba, serta dokter istana Dinasti Almohad. Namun, kebesarannya terletak pada karya-karya filsafatnya yang mengguncang pemikiran Eropa. Dalam Fasl al-Maqal, Ibnu Rusyd memperjuangkan keseimbangan antara akal dan wahyu, menunjukan bahwa filsafat dan agama bisa saling mendukung. Tahafut al-Tahafut, tanggapan terhadap kritik Al-Ghazali terhadap filsafat, menjadi pembelaan kuat untuk pentingnya berpikir logis. Tulisannya tentang karya Aristoteles, yang diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad ke-12, memengaruhi pemikir Kristen seperti Thomas Aquinas dan membentuk cara berpikir ilmiah Eropa.
Selain filsafat, Ibnu Rusyd menulis Kuliyat Fi At-tib, sebuah ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan universitas Eropa hingga abad ke-16. Pengaruhnya begitu besar sehingga Dante Alighieri menyebutnya dalam Divine Comedy sebagai “komentator Agung” Aristoteles. Di Indonesia, pemikiran Ibnu Rusyd sering dikaji dalam studi filsafat Islam. Harun Nasution dalam filsafat Islam, memuji pendekatan rasionalnya yang relevan dengan wacana modernitas. Di pesantren, nama Ibnu Rusyd dikenal sebagai simbol keunggulan intelektual Islam, sebagaimana dicatat dalam Sejarah Kebudayaan Islam karya Ahmad Syalabi. Warisannya mengajarkan bahwa keimanan dan keilmuan dapat berjalan seiring sebuah pelajaran abadi bagi umat Islam.
Al-Zahrawi: Bapak Bedah Modern dari Cordoba
Di dekat Cordoba, pada 936 M, lahirlah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang dikenal di Barat sebagai Abulcasis. Sebagai tabib istana kekhalifahan Umayyah, Al-Zahrawi merevolusi dunia kedokteran dengan Al-Tasrif li Man ‘Ajiza ‘an At-Ta’lif, ensiklopedia medis 30 jilid yang mencakup bedah, farmakologi, dan perawatan pasien. Bagian tentang bedah, yang diterjemahkan ke Latin pada abad ke-12, yang menjadi buku teks standar di universitas Eropa hingga abad ke-17. Al-Zahrawi memperkenalkan teknik bedah seperti penggunaan catgut untuk jahitan dalam alat-alat seperti skalpel, gunting bedah, dan spekulasi yang masih digunakan hingga kini.
Karyanya tidak hanya teknis, tetapi juga humanis. Ia menekankan pentingnya etika dokter, seperti memperhatikan kenyamanan pasien dan kebersihan alat. Pengaruhnya di Eropa terlihat dari adopsi tekniknya di Italia dan Prancis, sebagaimana dicatat dalam sains Eropa. Di Indonesia, Al-Zahrawi sering disebut sebagai “bapak bedah modern” dalam literatur sejarah sains Islam. Buku peradaban karya Badri Yatim yang populer di madrasah, memuji kontribusinya sebagai keunggulan Islam dalam sains. Artikel di NU Online juga kerap menyoroti Al-Zahrawi sebagai inspirasi bagi generasi muda untuk menggabungkan ilmu dan akhlak. Warisannya menunjukan bahwa inovasi lahir dari dedikasi dan kepekaan terhadap kemanusiaan.
Ibnu Al-Baitar: Maestro Farmakologi Islam
Lahir pada tahun 1197 M, Ibnu Al-Baitar adalah botanis dan farmakolog terkemuka di Al-Andalus. Terlatih di Sevilla, ia bepergian ke Afrika Utara dan Timur Tengah untuk mengumpulkan pengetahuan tentang tumbuhan. Karya utamanya, Kitab Al-Jami’ fi Al-Adwiya Al-Mufrada, adalah ensiklopedia farmakologi yang merangkum 1.4000 tumbuhan, mineral, dan obat-obatan. Ia mengintegrasikan pengetahuan Yunani, Romawi, dan Islam, juga menambahkan observasi empirisnya sendiri. Karyanya diterjemahkan ke Latin, menjadi rujukan di Eropa hingga abad ke-18 dan mempengaruhi perkembangan farmasi Barat.
Pendekatan ilmiah Ibnu Al-Baitar yang mengutamakan pengamatan langsung, mencerminkan semangat keilmuan Islam. Ia juga menulis Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiya Al-Mufrada yang fokus pada pengobatan spesifik. di Indonesia, kontribusinya sering dibahas dalam kajian sejarah sains Islam. Buku sumbangan Islam kepada sains karya Raghib As-Sirjani yang banyak di baca di pesantren, memuji Ibnu Al-Baitar sebagai pelopor farmakologi. Media seringkali menyebutnya sebagai contoh keunggulan ilmuwan Muslim. Warisannya menginspirasi umat Islam untuk menghidupkan tradisi keilmuan yang berbasis riset dan eksplorasi.
Ketiga ulama ini hidup pada masa keemasan Al-Andalus, yaitu ketika Cordoba menjadi kota paling maju di Eropa dengan perpustakaan yang menyimpan ratusan ribu manuskrip yang melahirkan ilmuwan kelas dunia. Namun, kejatuhan Al-Andalus pada tahun 1492 M ditandai dengan penaklukan Granada tidak memadamkan cahaya mereka. Karya-karya mereka yang diterjemahkan ke Latin terus dipelajari di universitas Eropa. Hal ini membuktikan bahwa Islam pernah menjadi lentera peradaban Barat. Pengaruh mereka terlihat dalam filsafat skolastik, teknik bedah, dan farmasi, yang menjadi fondasi kemajuan Eropa.
Di Indonesia, warisan ulama Al-Andalus memiliki makna mendalam. Ibnu Rusyd mengajarkan pentingnya keseimbangan antara akal dan iman, sebuah prinsip resonan dengan wacana Islam Nusantara yang moderat. Al-Zahrawi mengingatkan bahwa ilmu harus diimbangi dengan akhlak, sebuah nilai yang dijunjung tinggi di pesantren. Ibnu Al-Baitar menunjukan bahwa eksplorasi ilmu adalah ibadah, karena dapat menginspirasi generasi muda untuk berinovasi.
Ulama Al-Andalus adalah lentera peradaban yang tak hanya menerangi Eropa di abad pertengahan, tetapi juga terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini. Ibnu Rusyd, melalui filsafatnya, merangkai jembatan antara akal dan wahyu; Al-Zahrawi, dengan keahliannya di bidang bedah, menyelamatkan jiwa; dan Ibnu Al-Baitar, lewat ilmu farmakologinya, menyembuhkan raga.
Warisan mereka yang abadi, tersimpan dalam manuskrip dan terjemahan, menjadi bukti bahwa Islam pernah berdiri sebagai tiang utama peradaban dunia.
Bagi Indonesia, kisah para ulama Al-Andalus adalah panggilan untuk membangkitkan kembali semangat keilmuan dan keimanan sebuah warisan intelektual yang dahulu bersinar gemilang di Cordoba. Dengan mengenang cahaya Al-Andalus, kita diajak untuk menjadi pelita bagi zaman kita sendiri.
Referensi:
Shalabi, Ahmad. 2000. Sejarah Kebudayaan Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Nasution, Harun. 1987. Filsafat Islam. Jakarta: UI Press.
As-Sirjani, Raghib. 2010. Sumbangan Islam kepada Sains. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
Yatim, Badri. 2003. Peradaban Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kontributor: Neng Anggi Nur’aliah
Editor: Kurniawati Musoffa